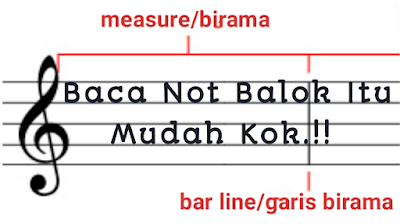Filsafat Seni Chapter 4: Esoterik dan Transendental
Eksistensi: Esoterik dan Transendental
Filsafat Seni - “Mengapa manusia memahatkan paraf (tanda tangan) mereka pada kulit kayu tua atau menggoreskannya pada dinding-dinding batu? Apakah yang membuat anak-anak melacak kembali jejak-jejak mereka pada pasir yang basah dengan melihat dengan sungguh-sungguh bekas telapak kaki mereka, menggerakkan pensil mereka di sekeliling jari-jari mereka untuk membuat garis kontur tangan mereka di atas kertas, atau menekankan tangan pada kaca jendela yang kena uap untuk menghasilkan siluet?Kita mengatakan “Engkau mengenai tangan dari sang pemilik”… Secara figuratif seniman meninggalkan pada anak-cucu bekas dari tangannya. Ia mengalihkan sebagian dari dirinya pada benda, membuatnya tampak, dan memberinya eksistensi yang terpisah dari dirinya”.
Permasalahan keberadaan, ke-menjadi-an, atau eksistensi.adalah suatu hal yang inheren dalam berkesenian. Hal ini juga telah menjadi sebuah subjek favorit dalam seni kontemporer. Seni pun dianggap sebagai salah satu sarana paling jitu untuk manifestasi keresahan, pencarian atau pertanyaan akan keberadaan tersebut.
Bagaimana keberadaan ini direpresentasikan pada kecenderungan-kecenderungan praktek seni (rupa) sekarang menjadi satu hal yang menarik yang sedikit banyak berakar pada kredo seni modern itu sendiri yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai ragam implementasi penandaan, pengolahan estetika dan substansi karya seni rupa.
Modernisme adalah sebuah ideologi yang mendominasi dan merasuk sampai ke pembentukan pola hidup dan budaya masyarakat global sepanjang abad 20.
Mimpi besarnya adalah kemerdekaan individu untuk mencapai kondisi paripurna dan mandiri dari kelemahan dan ketergantungannya kepada hal-hal ‘hakiki’ seperti kuasa alam, tubuh dan juga konstruksi-konstruksi primordial yang sebelumnya berlaku.
Keberadaan subjek adalah suatu hal yang sakral karena dengan modernisme, sempat hadir suatu harapan besar bahwa manusia dapat seperti yang terrumuskan pada pembedahan subjektivitas atau subjectivity seperti yang beberapa kali dipermasalahkan dalam wacana eksistensialisme.
Subjectivity atau subjektivitas menekankan penolakan terhadap konsep Cartesian akan cogito (human mind) sebagai sebuah pusat kendali sentral di mana kemudian makna terhasilkan. Singkatnya, subjectivity mencoba untuk melihat bagaimana manusia terbentuk sebagai subyek, sebuah sudut pandang untuk mengetahui bagaimana identitas terbentuk dengan mengakui peran wacana, pengetahuan, sejarah dan konstruksi-konstruksi lain di dalamnya, yang tak terkontrol oleh si subyek itu sendiri.
Dalam perspektif ini, subyek terkungkung dengan konstruksi-konstruksi yang telah ada namun sekaligus juga selalu terbuka dengan transformasi dengan semakin ia meleburkan diri dengan dunia luar, dan proses transformasi dalam diri subyek yang tak berkesudahan inilah yang akhirnya membuat perbedaan masing-masing subyek.
Seperti halnya makna yang selalu bergeser dari tandanya, begitu juga manusia sebagai subyek.
Dalam konteks Indonesia, kredo modernisme selalu berbenturan dengan primordialisme yang berakar pada masyarakat Indonesia yang bagaimana pun tak dapat serta-merta lepas dari pola kehidupan agrikutural dan komunalnya.
Pemahaman akan subjek sebagai suatu entitas yang mandiri atau munculnya otonomi pribadi dalam penciptaan karya seni menghasilkan perubahan besar dalam metode dan makna berkesenian si pencipta.
Hal ini dinyatakan dengan jelas melalui pengamatan historian yang telah sah namanya sebagai salah satu ‘pembingkai’ konstruksi sejarah seni rupa Indonesia, Claire Holt, dalam thesis besarnya ‘Art in Indonesia: Continuities and Change’, sebuah pembacaan besar dan linear seperti yang dia uraikan berikut ini:
“Pada seni rupa, setelah satu masa sejuk dari latihan-latihan dalam pembuatan-pembuatan draft serta lukisan naturalistic, sebuah terobosan terjadi, seperti telah kita saksikan, dengan tujuan utama penonjolan diri.
Munculnya pribadi yang belum pernah terjadi dalam karya-karya para pelukis selama dan setelah perang, adalah satu dari fenomena signifikan yang perlu diperhatikan. Di Jawa penonjolan “Saya adalah” yang diikuti dengan pertanyaan “Siapakan Saya?” terrefleksikan dalam potret-potret diri dari gaya-gaya yang berbeda serta ungkapan-ungkapan perasaan yang berbeda.
Dengan demikian Affandi dalamn sketsa ekspresifnya :”Belajar Melukis Diri Sendiri” (dibuat pada tahun 1944) tampil sebagai yang vital dan yang yakin seperti pada kaligrafinya.
Tubuh yang lemah serta wajah yang letih pada Sudibio pada sebuah latar belakang sunyi (dibuat tahun 1949) adalah kemurungan yang berbusana putih.
Tarmizin yang tuli berbicara pada kita dengan keremajaan serta kelembutan dari potret diri tahun 1955, matanya yang penuh perhatian dengan mengandung pertanyaan tersesuaikan dengan perbedaan yang tak kentara dari bentuk-bentuk dan warna-warna”.
Hal ini akhirnya menjadi sebuah medan pergelutan semiotika subjektivitas yang begitu kaya dan riuh-rendah dalam penciptaan karya seni, dalam hal ini juga seni rupa.
Sampai dari lebih setengah abad sejak ‘sang subjek’ menjadi materi dalam penciptaan karya di seni rupa Indonesia, ia dikukuhkan menjadi sebuah subject-matter yang sah, memberi jalan bagi ekspresi dan pemaknaan subjek, walau juga tak dapat dikatakan tanpa kerancuan dan paradoks, dan pada akhirnya, berlainan dengan pakem Holt, tak dapat lagi dibaca secara linear, naratif mau pun literer.
Ekspresi eksistensi sang subjek tak lagi sesederhana seperti menghantarkan kisah-kisah yang tergambar melalui potret diri, melainkan asemblase dari berbagai kompleksitas subjektivitas sang pengkreasi tersebut.
ST Sunardi dalam bukunya “Semiotika Negativa” (2003), sebuah pembacaan terhadap Barthes dan Baudrillard yang kemudian ia gunakan untuk menjelaskan relasi-relasi ekspresi subjektivitas manusia modern dalam proses penciptaan karya seni rupa kontemporer dan arus budaya visual, terutama di Indonesia.
Pembahasaan subjektivitas seperti ini terutama terlihat pada Bab II Semiotika Negativa: bagian ‘Bahasa/Wicara dan Budaya’.
Secara khusus disini, Sunardi melakukan sebuah perumusan pembacaan terhadap kecenderungan yang terjadi dalam praktek seni dan budaya visual kontemporer sekarang ini, dimana seperti pembacaannya terhadap Baudrillard dan Barthes serta apa yang disebut Barthes sebagai sebuah ‘transgresi kreatif’ atau ‘creative transgression’ yang menjadi gejala kreativitas dalam pelaku pengkaryaan kontemporer.
Menurut Sunardi, Creative Transgression ini dapat dipakai untuk menilai kreativitas kultural yang terjadi pada zaman sekarang dimana terjadi silang-sengkarut antara nilai, makna dan tanda. Ia memberikan contoh, “Dalam wayang misalnya, musik dangdut dan/atau band (DD & BN) dimasukkan ke dalam alur kisah wayang.
Musik ini menjadi satuan baru di antara satuan-satuan musik lainnya. Baudrillard memperhatikan bahwa budaya modern ditandai dengan pengumpulan barang tanpa orang tahu atau tanpa mau tahu fungsinya. Inilah yang ia sebut non-functional.”
“Eksistensialisme a’la Indonesia” ini menciptakan berbagai dimensi dan karakteristik pengkaryaan di mana tanda, makna nilai dan fungsi menjadi ambigu yang tidak pula lagi percaya – atau mungkin juga memang tak pernah sepenuhnya percaya, secara sadar atau tidak - pada idealisasi modernisme.
Karya seni bukan jawaban, menjadi manifestasi fragmen-fragmen subjektivitas atau kepingan puitisasi dari subjektivitas tersebut. Dimensi atau alur transgresi kreatif itu dapat dilihat dari karya-karya seni rupa dari generasi yang berbeda yang secara beragam memperlihatkan tegangan-teganga, antara tradisi dan modernitas, primordial dan sekularitas.
Analisa semiotika seperti di atas itulah yang kemudian dapat mendasari acuan dalam pembacaan kecenderungan manifestasi kreatif pada 2 kategori kecenderungan pengkaryaan seni rupa dalam pameran ini yaitu: Eksistensi: Transendental, dan Eksistensi: Esoterik. Kompilasi dalam Eksistensi:
Transendental adalah sebuah asemblase yang memperlihatkan kecenderungan akan manifestasi diri dalam konteks spiritualitas yang melampaui diri tersebut, sementara Eksistensi:
Esoterik adalah sebuah plethora penjelajahan subjektivitas dalam karya seni rupa yang melampaui representasi-representasi atau ‘kaidah-kaidah harafiah’ dalam penandaan diri.
Dalam konteks ini, kedua kategori tersebut sejajar dan saling juga bisa berinterrelasi satu sama lain, menyiratkan sebuah hasrat penemuan keseimbangan pencarian keberadaan tersebut, sebuah equilibrium antara kesadaran akan diri dan juga kegelisahan naluriah akan ‘The Higher Self/Entity’, sesuatu yang, rupanya, menjadi salah satu karakteristik paling menonjol di masyarakat Indonesia.
Sepasang subject-matter yang sepertinya akan selalu dan tak akan habis digali dalam praktek pengkaryaan seni rupa negeri ini.
Penandaan Eksistensi Melalui Subjektivitas Transendental
Praktek ini di satu sisi merupakan hasil jukstaposisi penerjemahan fungsi seni modern sebagai pencarian yang ideal dengan fungsi seni rupa secara primordial bahwa seni, bagaimana pun tetap merupakan ekspresi penyerahan diri akan tetap berada di bawah ‘sang ideal’ tersebut, dalam hal ini pengaruh religiositas dan kepercayaan terhadap ‘campur tangan Ilahi” atau “Cinta Ilahiyah” menjadi stimulan utama penciptaan. Sesuatu yang sebenarnya telah berkembang sejak kesenian masih disebut sebagai “seni tradisional” yang menjadi karakteristik masyarakat agraris dan pagan.Dalam dinamika budaya kontemporer, hal ini berkembang dalam seni rupa dengan mencampuradukkan elemen-elemen antara subjektivitas diri tersebut dengan nilai-nilai spiritual di luar dirinya, sebuah “spiritual creative transgression” yang sedikit banyak mencerminkan “metode ekspresi sufistik” yang banyak juga tersirat dalam karya-karya sastra religius modern.
Sebuah permainan intertekstual antara elemen-elemen subjektivitas dan hubungan manusia dengan ‘Yang Di Atas’.
Manusia langsung dapat berkomunikasi dengan Tuhan/Alam dan mengekspresikan ke-Ilahi-an melalui subjektivitasnya sendiri, dan seni rupa memberikan sarana yang sangat lezat untuk itu, seperti yang dapat dilihat dalam karya-karya antara lain I Nyoman Erawan yang sejak dulu secara kukuh menjadikan ini sebagai subject-matter-nya.
Metafor buku dan kertas Setiawan Sabana, ritme objek dan ruang dalam figure-figur batu melayang Yani Mariani, Nunung WS dengan abstraksi warnanya, dan lain-lain dalam kompilasi ini.
Penandaan Eksistensi melalui Subjektivitas Esoterik
Dalam kamus Mirriam Webster, ‘Esoteric’ atau ‘Esoterik’ dimaknai sebagai : “1 a: designed for or understood by the specially initiated alone (a body of esoteric legal doctrine — B. N. Cardozo) b: requiring or exhibiting knowledge that is restricted to a small group (esoteric terminology); broadly : difficult to understand (esoteric subjects); 2 a: limited to a small circle (engaging in esoteric pursuits) b: private, confidential (an esoteric purpose)”.Kecenderungan esoterik dalam karya seni rupa terutama oleh generasi perupa pasca 90-an adalah salah satu cermin gelaja ekspresi subjektivitas yang sebagian secara sadar ingin bebas dari verbalisme dan metafora naratif dalam merepresentasikan diri dan jiwa, dan sebagian lagi secara tidak sadar adalah hasil penyerapan visual akan ikon-ikon dalam budaya visual kontemporer yang sarat ‘polusi visual’, yang kemudian direspon oleh perupa dengan menciptakan ‘ikonografi personal’ dengan sistem penandaan dan pemaknaan yang sangat terfragmentasi.
Ekpresi eksistensi esoterik adalah juga refleksi hasrat perupa untuk berkomunikasi namun dengan strategi ex-komunikasi, visualisasi yang berjarak terhadap diri sendiri. Daya tarik dari keberjarakan ini justru yang menciptakan relasi antara si karya dan audiens, karena memberikan sebuah nuansa sublim atau bisa juga surreal yang menggelitik untuk diraih namun tak pernah bisa sepenuhnya.
Permainan tekstual keberadaan ini seperti tergambar dalam karya-karya Eko Nugroho dengan lingo Daging Tumbuhnya yang telah menjadi ikon visual baru seni rupa kontemporer, Davy Linggar dengan alienasi objek dalam foto, dan Ay Tjoe Christine yang menggoreskan bagian-bagian dirinya melalui dry-point, kompilasi ini yang dapat juga disebut sebagai ‘perayaan non-verbal’, atau,merombak sedikit kutipan dari Claire Holt di atas, “Keberhasilan para perupa dalam mengalihkan dirinya pada benda (rupa), membuatnya tampak, dan memberinya eksistensi yang (jauh) terpisah dari dirinya”.